Sebulan yang lalu, trailer “The Little Mermaid” (2023) dirilis Walt Disney Studios memancing reaksi publik. Penampilan Halle Bailey, seorang aktris berkulit hitam, yang berperan sebagai Ariel, dipandang melenceng dari imaji Ariel versi animasi yang berkulit putih dan berambut merah.
Warganet merespon ketidaksukaan mereka terhadap Halle Bailey dengan memviralkan tagar #NotMyAriel, sebagai protes terhadap representasi paksa (forced representation) dalam adaptasi “The Little Mermaid” ini.
Selain memantik protes warganet, polemik ini juga memantik diskursus mengenai representasi dalam Hollywood. Keterpilihan Halle Bailey juga mendapat dukungan dari sebagian orang. Ia dianggap telah membuka dunia yang penuh dengan kesempatan dan peluang serta membuat senang masyarakat Afrika-Amerika.

Ketika representasi mendapatkan dukungan dalam dunia Hollywood, beberapa penulis memberikan catatan bahwa tidak setiap usaha yang telah dilakukan berhasil mewujudkan keberagaman. Salah satu hal yang perlu diperhatikan perihal representasi adalah tokenisme, yakni penggunaan kelompok minoritas hanya sebagai pelengkap semata. Dalam banyak kasus, media terjebak dalam perangkap misrepresentasi yang hanya menjadikan minoritas hanya sebagai piala pajangan.
Polemik terhadap representasi minoritas dalam Hollywood dapat ditarik sejak kemunculan sinema di Amerika Serikat. Richard W. Waterman dalam artikel berjudul The dark side of the farce: racism in early cinema, 1894-1915 mengatakan bahwa banyak film yang muncul pada awal kemunculan sinema penuh dengan stereotip rasial terhadap masyarakat minoritas.
Masyarakat kulit hitam ditampilkan sebagai sosok yang serba-jahat atau dungu (nitwit) dan berperilaku kekanak-kanakan. Dalam film The Birth of a Nation (1915), masyarakat kulit hitam, yang diperankan oleh aktor kulit putih dengan blackface, ditampilkan sebagai sekumpulan badut yang bodoh dan agresif terhadap wanita kulit putih. Selain ditampilkan demikian, mereka diposisikan sebagai sosok antagonis, serba-jahat, yang ditaklukkan oleh kelompok kulit putih yang mempertahankan nilai adiluhung masyarakat Amerika.

Selain menampilkan stereotip rasial terhadap masyarakat kulit hitam, sinema Amerika Serikat saat itu juga dipenuhi dengan stereotip rasial terhadap masyarakat Asia. Sepanjang 1910-an hingga 1940-an, Hollywood menciptakan stereotip “kelompok Oriental yang sulit dipahami” (Inscrutable Oriental) terhadap masyarakat Asia-Amerika. Menurut Sriganeshvarun Nagaraj dan Chien Puu Wen dalam artikel Asian stereotypes: Asian Representation in Hollywood Films, masyarakat Asia diposisikan sama seperti masyarakat kulit hitam, yakni sama-sama diposisikan sebagai tokoh antagonis dan hanya mendapatkan peran yang tidak menonjol, seperti pelayan, pekerja kasar, koki, dan lainnya.
Dalam beberapa kasus, Hollywood memberlakukan apa yang dikenal sebagai whitewashing dalam industri perfilman. Whitewashing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan pelaku industri film Amerika Serikat dengan menggunakan aktor kulit putih terhadap peran-peran tokoh kulit berwarna. Hal ini dilakukan sebagai wujud supremasi kulit putih pada abad ke-20, mengutip John Whitson Cell dalam buku The Highest Stage of White Supremacy. Beberapa contoh whitewashing yang pernah dilakukan Hollywood antara lain John Wayne yang memerankan Genghis Khan dalam film The Conquerer (1956) dan Johnny Depp yang memerankan Tonto, seorang Native America, dalam film The Lone Ranger (2013).
Lalu, bagaimana wujud representasi kelompok minoritas dalam Hollywood dewasa ini? Bisa dikatakan, sineas Hollywood berada dalam garis antara tokenisme (tokenism) dan keberagaman (diversity). Dalam beberapa film, Hollywood berhasil tidak hanya menggunakan aktor dari kelompok minoritas sebagai pemeran utama dalam film, tetapi juga mampu menampilkan keberagaman budaya yang hidup dalam masyarakat. Film seperti Moonlight (2016) dan Black Panther (2017) tidak hanya menampilkan Mahershala Ali dan Chadwick Boseman sebagai tokoh sentral, tetapi juga mampu memberikan gambaran kepada penonton dinamika kehidupan masyarakat kulit hitam serta kebangaan memiliki darah keturunan Afrika.

Di sisi lain, Hollywood terlihat kesulitan dalam menerapkan representasi dalam industri perfilman. Dalam Stranger Things (sejak 2016), Lucas Sinclair yang diperankan oleh Caleb McLaughlin hanya ditampilkan sebagai pelengkap tokoh lainnya. Ia tidak memiliki kisah yang mampu ditampilkan dari sudut pandangnya sebagai seorang remaja berkulit hitam dalam sebuah kelompok remaja kulit putih. Contoh serupa juga terjadi dalam film A Wrinkle in Time (2018), yang menampilkan perempuan, sebagai salah satu simbol representasi dalam dunia yang patriarki, hanya sebagai “check box” semata, membuat seolah-olah film tersebut berhasil mewujudkan sebuah representasi.
Sebagai sebuah hal yang menjadi tuntutan dari masyarakat Amerika arus bawah serta trauma masa lalu, menampilkan keberagaman merupakan sebuah tuntutan yang sedapat mungkin bisa dilakukan oleh Hollywood. Sebuah tuntutan yang perlu diperhatikan dengan saksama oleh para pembuat film, terlebih pada masa sekarang. Salah dalam bertindak dan membangun representasi dapat mempengaruhi penjualan film.
Membangun keberagaman secara natural, seolah ia menjadi bagian dari film dan bukan dipaksakan demi kepentingan marketing, merupakan sebuah keharusan. Namun demikian, semua penonton film lebih senang dengan film yang bagus. Meskipun ada desakan untuk menerapkan representasi, film yang dihadirkan tetap harus menghibur, karena ia merupakan produk yang berfungsi menghibur penikmatnya.
Sumber : CXOMedia; Monitor Daily; The State News; Cosmopolitan UK; The State Press; The Philadelphia Inquirer; Concrete Online; Richard W. Waterman, The dark side of the farce: racism in early cinema, 1894-1915; Sriganeshvarun Nagaraj dan Chien Puu Wen, Asian stereotypes: Asian Representation in Hollywood Films; John Whitson Cell, The Highest Stage of White Supremacy; Huffpost; BBC; The Guardian (1), (2); Smithsonian Magazine; MEGA Magazine.
Putu Prima Cahyadi
Facebook : Prima Cahyadi
Email : prima.cahyadi.p@mail.ugm.ac.id





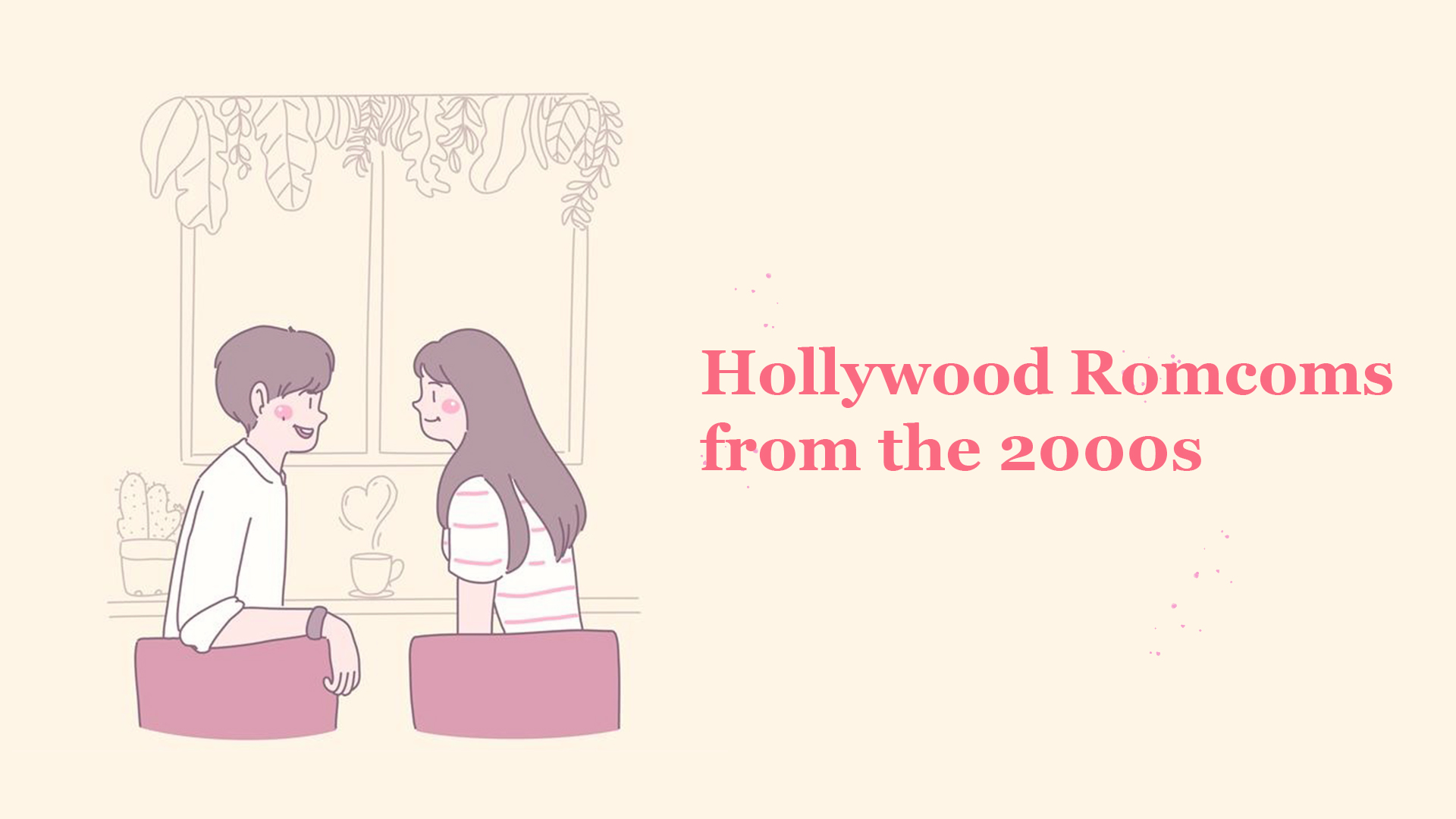



Hmmm, kayaknya isi artikelnya ga pertimbangkan sama sekali unsur white supremacist dari yang kontra dalam film ini tersendiri. Apalagi kalau telusuri tagar notmyariel yang dipenuhi dengan hate speech dan rasisme.
[…] karakter (blackwashing) tidak hanya terjadi dalam film-film Hollywood, seperti The Little Mermaid atau Snow White saja. Ia juga terjadi dalam dunia […]