“Orang gila,” ungkap seorang bernama Reza Fold dalam grup Facebook Penyefong Western (Menolak Degenerasi) menyindir Nino Coser. Dalam postingan tersebut, ia menyerang Nino Coser, seorang crossdresser, yang melakukan unfriend dan blokir massal terhadap warganet yang menyebutnya sebagai homoseksual di internet.
Postingan tersebut mendapatkan respon seragam oleh anggota grup yang terkenal membenci apa pun berbau LGBTQ tersebut. Mengutip komentar Yahya Candra Atmadin, ia menyarankan kepada siapa saja yang masih satu daerah dengan Nino Coser untuk mengirimkan “kepala tangan yang diayunkan secara cepat” ke kepalanya, agar menjadi lebih waras.

Komentar seperti itu, bagi Nino Coser, sudah menjadi sarapan pagi. Sebagai buah kuldi asal Samarinda, nama yang sering disematkan oleh pembenci kepadanya, tindakannya yang gemar melakukan cosplay crossdressing dihujat. Mereka memandang hal tersebut sebagai penyimpangan, dan suara terhadap kaum LGBTQ. Mengapa crossdressing dalam dunia cosplay di Indonesia ditentang saat ini?
Fenomena crossdressing bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak masa kebudayaan Hindu-Buddha, golongan laki-laki yang berpakaian perempuan (kd̩i) sudah dikenal dalam perjalanan sejarah negara ini. Mengutip Muhammad Alnoza dan Dian Sulistyowati dalam artikel Konstruksi Masyarakat Jawa Kuno terhadap Transgender Perempuan pada Abad ke-9-14 M, kd̩i dipandang sebagai manusia yang memiliki disabilitas dan menjadi sasaran diskriminasi dalam hukum kerajaan.
Meski menjadi korban diskriminasi, beberapa seniman Indonesia memilih untuk menampilkan kesenian Indonesia dengan crossdressing. Sebut saja Didik Nini Thowok, seniman tari asal Indonesia yang menampilkan kesenian crossdressing sejak 1980-an. Menurut Felicia Hughes-Freeland dalam artikel Cross-Dressing Across Cultures: Genre and Gender in the Dances of Didik Nini Thowok, Didik berhasil menyajikan dan menunjukan kepada masyarakat bahwa crossdressing tidak melulu soal menjadi transpuan.

Lalu, bagaimana dengan cosplay crossdressing (crossplay) di kalangan para cosplayer? Sejak 2010-an, sosok Haoge tidak dapat dipisahkan dengan tren crossplay. Haoge, sebagai seorang crossplayer, cosplayer yang menggunakan kostum karakter jenis kelamin yang berbeda, menginspirasi beberapa cosplayer untuk menjadi crossdresser. Sebagaimana dikutip melalui Joanito Pereira Da Silva & Nunuk Endah Srimulyani dalam artikel Pemaknaan Gender dalam Kegiatan Crossplay MtoF oleh Tiga Anggota Komunitas Cosplay Community Cosura Surabaya, seorang informan bernama Chiusa menyatakan:
“Di media sosial banyak [crossplay], terutama saya menemukan seorang crossplayer MtoF yang bernama Haoge, yang saya suka dari Haoge adalah karena cantik dan kelihatan mirip, cocok sama karakternya. Saya melakukan crossplay karena saya suka dengan karakter yang saya sukai, dan tujuan saya hanya bersenang-senang saja, tidak ada yang lain.”
Masih menurut Da Silva & Srimulyani, seorang crossplayer merasa bahwa kegiatan mereka hanyalah kegiatan personal, selain untuk menghibur para penikmat cosplay dan crossplay. Meski harus menyembunyikan hobi tersebut dari orangtuanya, Chiusa mengakui bahwa crossplay memberikan dampak positif dan rasa kepuasan tersendiri yang tidak bisa dia dapatkan melalui cosplay biasa. Lebih lanjut, Chiusa mengungkapkan bahwa ia merasa dirinya “lebih cantik dan lebih imut” melalui crossplay.

Jika crossplay atau crossdressing tidak memiliki masalah krusial, mengapa masyarakat Indonesia seolah-olah antipati terhadap para crossdresser dan crossplayer? Mengutip Dan Silva & Srimulyani, crossdressing dilakukan bukan hanya sebagai hobi semata. Tidak ada suara dukungan terhadap LGBTQ yang mereka suarakan melalui kegiatan crossdressing dan crossplay.
Baik para crossplayer maupun crossdresser, mengutip Seta Lingga Whisnu dalam artikel Ekspresi Gender dalam Cosplay (Studi Deskriptif Kualitatif pada Cosplayer yang Melakukan Crossdress pada Komunitas Jaico Semarang), hanya melakukan crossplay dan crossdressing sebagai bermain peran semata. Meski begitu, mereka masih tetap mengalami diskriminasi. Mereka dipandang sebagai pendukung kelompok LGBTQ, meski crossplay dan crossdressing yang dilakukan tidak menggambarkan ekspresi gender yang sebenarnya.
Sebagai penutup, tidak serta merta crossdressing, baik dalam berkesenian maupun dalam cosplay, sebagai bentuk objektivitas dalam melihat seuah fenomena budaya pop. Sama seperti cosplay pada umumnya, crossdressing hanya menjadi sarana untuk menyalurkan hobi bermain peran dengan kostum karakter tertentu, dan tidak perlu lagi ditafsirkan.
Crossdressing dapat dilihat dari bagaimana berbagai kegiatan tersebut hanya dilakukan atas dasar hobi dan tanpa membawa pesan politik apa pun. Namun, kondisi ini tentu akan berbeda jika ada pesan politik, seperti penggunaan tagar (hashtag) tertentu. Sah-sah saja, bagi masyarakat, untuk menolak crossdressing seperti ini.
Disayangkan, stigma yang melekat terhadap crossdressing saat ini membuat banyak orang memilih untuk tidak melakukannya. Dalam kasus Nino Coser, perundungan yang ia terima dari berbagai pihak membuatnya harus mundur dan kehilangan tempat untuk mengekspresikan diri dengan bebas.



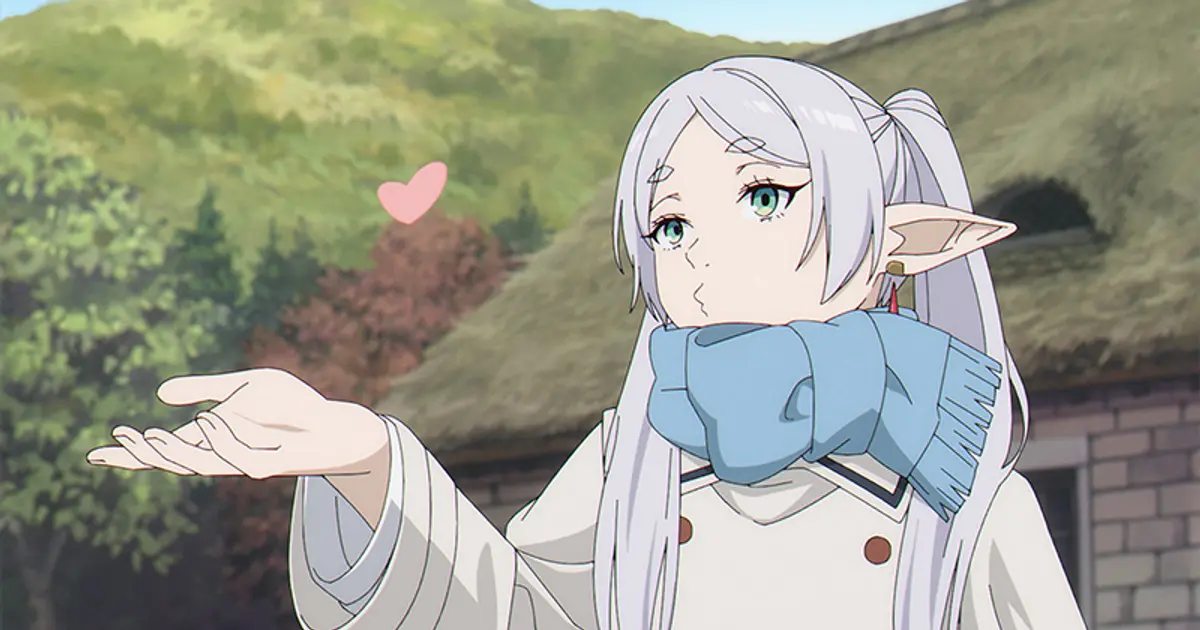





mantab artikelnya, iya kesian sumpah nino coser dibully sama wibu-wibu sok sok an, hipokrit semua ngaku si paling suci
Begitulah. Orang fokus nge-bully-nya dulu, gak menarik kasus Nino Coser lebih jauh
[…] Read More: Nino Coser dan Dilema Crossdressing dalam Kultur Budaya Populer Jepang di Indonesia […]