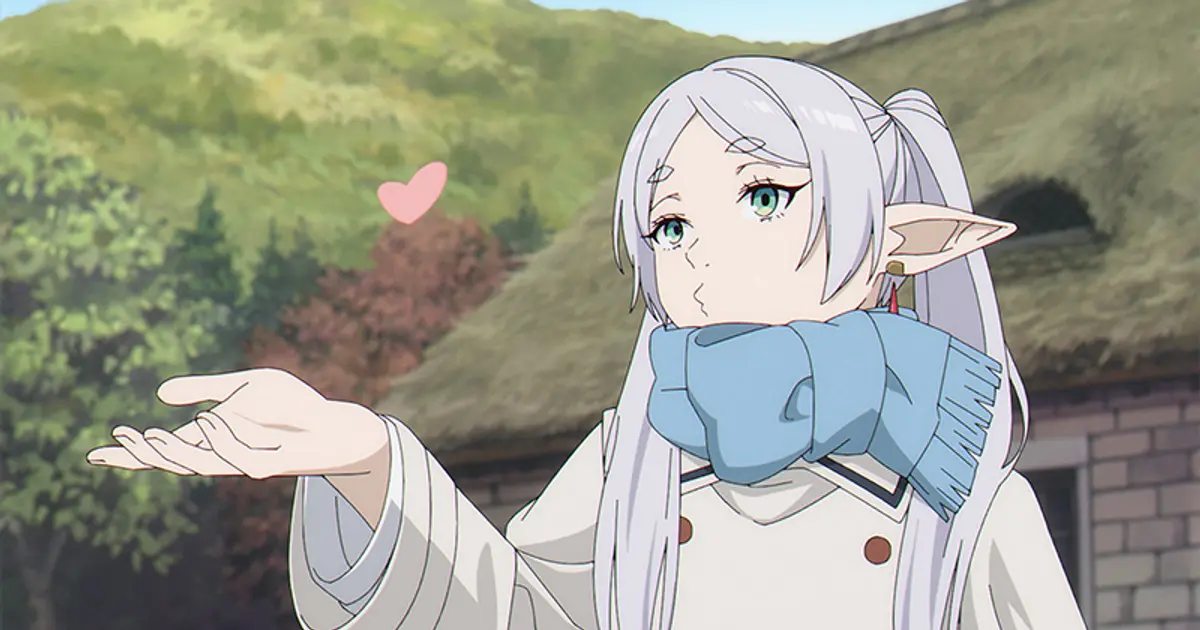“Meresahkan,” begitulah publik Indonesia melihat keberadaan sound horeg belakangan ini. Sound horeg, atau sebuah truk, mobil bak terbuka, atau motor, yang mengangkut banyak sound system besar dan mendendangkan lagu dengan desibel yang keras ini dianggap mengganggu ketertiban umum.
Seperti yang terungkap dalam artikel Fenomena “Sound Horeg” yang Dinilai Semakin Meresahkan oleh Faizal A., kehadiran sound horeg membawa dampak polusi suara yang memekakkan telinga. Musik yang dimainkan melalui sound system, yang terkadang bisa melebihi desibel suara yang dapat diterima manusia, dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, utamanya kerusakan pendengaran.
Selain mengganggu telinga, keberadaan sound horeg, yang terkadang berkeliling dari rumah ke rumah, seringkali harus merusak fasilitas umum. Sejumlah kaca dan genting rumah pecah berjatuhan, sebagai efek sound system yang terlalu keras. Tidak hanya itu, sebuah video di Malang menampilkan rombongan sound horeg membongkar sebuah jembatan, agar truk pengangkut sound system dapat melintas.
Kondisi di atas tentu memperkuat pandangan publik Indonesia akan sound horeg, yang semakin “meresahkan” dan dicitrakan serba-negatif. Namun, sebagai sebuah produk budaya populer, kehadiran sound horeg belum banyak disinggung masyarakat. Bukan hanya sekadar budaya yang meresahkan, sound horeg juga bisa dilihat sebagai bagian dari budaya masyarakat di daerah dalam mengimplementasikan budaya diskotek masyarakat urban versi budget.
Dari Sound System Rumahan menjadi Diskotek Pinggir Jalan
Sebagai sebuah fenomena, sound horeg bukanlah hal baru di Indonesia. Ia berkembang dari beberapa budaya bermusik masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah ke bawah.
Mengutip sebuah artikel berjudul Mengenal Fenomena Sound Horeg oleh Rafi Alvirtyantoro, kehadiran sound horeg telah ada sejak dekade 2000-an. Saat itu, masyarakat menggunakan alat pengeras suara sebagai sarana hiburan sederhana. Mereka memutar musik, berjoget, dan berdendang ria sesuai dengan keperluannya.

Masih menurut artikel yang sama, kehadiran sound horeg tidak lepas dari kebiasaan masyarakat di daerah kabupaten untuk memiliki sound system untuk kebutuhan seremonial, seperti selawatan, hajatan, dan lainnya. Hingga pada suatu hari, sebuah ide muncul untuk mengubah sound system tersebut menjadi sound horeg yang kita kenal sekarang.
Dari mana inspirasi tersebut muncul? Menurut Muhammad Rafi Azzamy, salah satu anggota tim peneliti dengan judul Model Rekayasa Sosial Transformatif untuk Memberdayakan Sound Horeg, perubahan sound system rumahan menjadi sound horeg terinspirasi dari tren diskotek di kota-kota besar. Seorang warga ingin merasakan hiburan serupa diskotek, tetapi dengan pendekatan yang lebih merakyat.

Keinginan tersebut, ditambah dengan kerinduan untuk merasakan hiburan di luar rumah ketika pandemi COVID-19, mendorong sound horeg tumbuh sebagai sebuah budaya. Ia menjadi semacam diskotek pinggir jalan, membawa musik, tarian, dan sorotan lampu sorot dari ruang tertutup ke jalanan.
Sound Horeg dalam Perdebatan SDM Rendah/SDM Tinggi
Keberadaan sound horeg dewasa ini memantik diskusi di kalangan warganet. Banyak dari mereka menuduh penggemar sound horeg sebagai SDM Rendah. Mereka beralasan bahwa sound horeg adalah hiburan bagi masyarakat kampungan, udik, dan tidak mendidik masyarakat.
Menanggapi kritik warganet yang bertebaran, pegiat sound horeg meresponnya dengan pernyataan 100% SDM Rendah. Seperti yang terlihat dalam sebuah postingan Reddit, tergambar jelas bahwa mereka mengaminkan kritik warganet perihal SDM rendah, sekaligus menyampaikan kritik kepada mereka ber-SDM tinggi. Suara mereka tegas: tidak ada urusan soal pernyataan SDM rendah, yang penting hiburan mereka tetap jalan.

Polemik SDM Rendah dan SDM Tinggi perihal sound horeg segera mengingatkan kita dengan polemik antara budaya tinggi (high culture) dan budaya populer (popular culture). Sebagai diskotek pinggir jalan, sound horeg adalah cerminan dari sebuah budaya populer yang merakyat. Ia lahir dari masyarakat, terutama masyarakat kebanyakan, dan disebarkan kembali untuk masyarakat.
Berbeda dengan diskotek dalam ruangan, yang hanya bisa diikuti mereka yang berduit atau memiliki akses, sound horeg dapat dinikmati oleh siapa saja dan di mana saja. Ia tidak terhalang batasan khusus, seperti diskotek dalam ruangan (high culture). Ia bisa berjalan dari rumah ke rumah, mengajak pemilik rumah untuk ikut berada dalam lantunan musik dan tarian para biduan.
Sebagai sebuah budaya yang populer, mudah dipahami, dan menghibur sebagian besar orang, sound horeg telah tampil sebagai lawan dari budaya diskotek. Ketika diskotek, sebagai high culture, hanya bisa diakses oleh segelintir orang, sound horeg menjadi semacam popular culture sekaligus alternatif bagi mereka yang ingin menikmati budaya diskotek, tetapi memiliki banyak keterbatasan.
Apakah Sound Horeg merupakan Sebuah Produk Budaya?
Pertanyaan terakhir yang mungkin masih tersisa dalam benak kita saat ini, apa benar sound horeg adalah sebuah produk budaya? Apakah fenomena yang lebih banyak digambarkan merusak genting dan kaca rumah ini dapat disebut sebagai sebuah budaya?
Mengutip Edward Burnett Tylor dalam Primitive Culture, budaya adalah sebuah sistem yang kompleks, terkait dengan pengetahuan, sistem kepercayaan, moral, hukum, dan adat istiadat yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, Kroeber dan Kluckhohn mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah abstraksi dari perilaku konkret manusia.

Dalam konteks ini, sound horeg adalah sebuah budaya, karena ia merupakan perwujudan dari perilaku konkret manusia, dalam hal ini masyarakat di kabupaten. Melalui perilaku mereka menggunakan sound system secara pribadi, serta keinginan untuk membawa budaya diskotek ke daerah mereka, mendorong terciptanya sebuah budaya baru, sound horeg.
Budaya tidak melulu harus dilihat serba-adiluhung atau sebuah budaya leluhur, seperti kita memahami wayang atau tarian tradisional sebagai produk budaya. Budaya juga merupakan sebuah hal yang berwujud lebih abstrak, seperti tradisi menunda-nunda waktu, menggunakan celana panjang dan t-shirt, atau makan dengan sendok dan garpu. Dalam hal ini, sound horeg adalah sebuah budaya dalam perwujudan abstrak, tidak terikat dengan ikatan budaya leluhur atau sesuatu yang adiluhung.
Terlebih, sejak tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan sound horeg sebagai kebudayaan. Melalui Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/144/KEP/35.07.013/2022 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sound horeg tercantum sebagai salah satu objek kesenian di Kabupaten Malang. Ini semakin menegaskan bahwa sound horeg, terlepas dari polemik yang ditimbulkannya, adalah sebuah produk budaya.
Pada akhirnya, sebagai diskotek pinggir jalan, sound horeg muncul sebagai sebuah kebudayaan, dalam hal ini budaya populer (popular culture). Terlepas dari polemik yang menyertainya, seperti menimbulkan kebisingan, polusi suara, hingga dituduh SDM Rendah, ia eksis sebagai hasil abstraksi tindakan manusia. Sebagai hasil perwujudan keinginan untuk menikmati diskotek dan kebiasaan menikmati musik melalui sound system, sound horeg tampil sebagai salah satu produk budaya populer yang lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia.